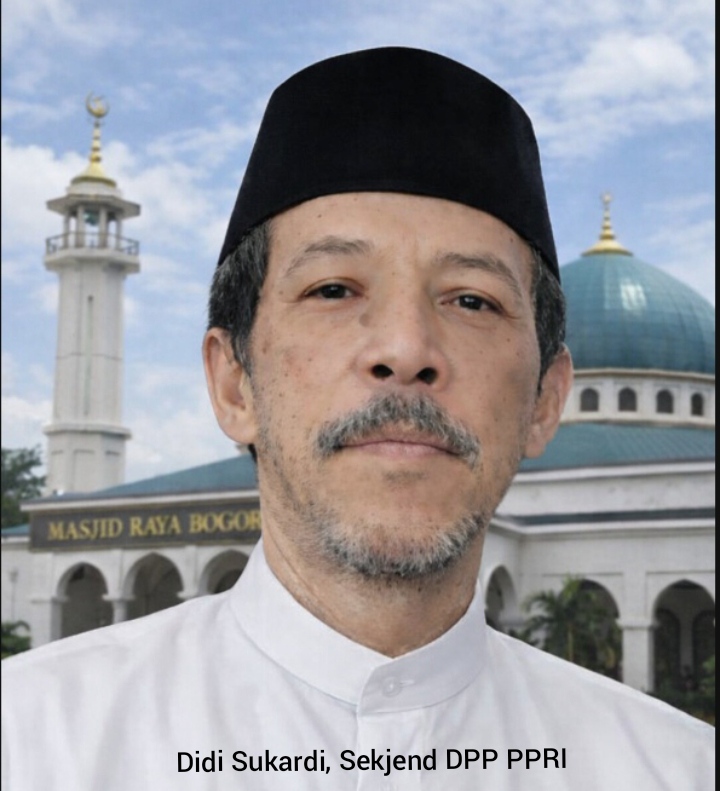Oleh Hendra Sudrajat, S.H.
DEFAKTO – Sudah lama media televisi kita kehilangan akal sehat. Di tengah upaya bangsa menjaga kehormatan tokoh agama dan lembaga pendidikan pesantren, masih saja ada stasiun televisi yang merasa lucu ketika martabat kiai dijadikan bahan lawakan. Rupanya, bagi sebagian kru layar kaca, segala hal bisa dijadikan komedi, bahkan sesuatu yang bagi umat adalah suci dan penuh adab.
Trans 7, yang dulu dikenal dengan tayangan berkualitas dan menghibur, kini seperti kehilangan arah. Alih-alih memperkuat literasi publik, mereka malah memilih menjadi corong lelucon murahan dengan risiko menampar wajah kiai dan santri. Barangkali, di ruang redaksinya, tepuk tangan bergemuruh saat ide “konten sensitif” itu disetujui. Tapi di luar sana, jutaan hati santri menangis dalam diam — karena kehormatan mereka dijadikan tontonan.
Lucunya, semua itu dibungkus dengan kata sakti: “kritik sosial”. Seakan-akan dengan memakai istilah itu, segala bentuk penghinaan bisa dimaafkan. Kritik, katanya. Padahal yang terdengar hanya cemooh, yang terasa hanya luka. Kritik mestinya membangun, bukan membakar harga diri. Tapi mungkin mereka tak lagi tahu bedanya antara satire yang mendidik dan satire yang menista.
Dan ironisnya, ketika umat menegur, mereka justru berlindung di balik kalimat “kita demokratis, semua boleh dikritik.” Betul. Semua boleh dikritik. Tapi tidak semua boleh dilecehkan. Demokrasi bukan panggung sarkasme untuk mempermalukan orang yang dihormati jutaan umat. Apalagi yang selama ini menjaga moral bangsa tanpa pamrih, jauh dari hingar-bingar popularitas media.
Sejak kasus di Sidoarjo mencuat, ada banyak pihak yang dengan senang hati menunggangi isu santri dan pesantren. Media, influencer, dan selebritas seolah berlomba mencari sensasi dari lumpur isu itu. Maka tak heran, video Trans 7 ini seperti memanfaatkan bara yang belum padam. Mereka tahu ini isu sensitif, tapi tetap disiram bensin. Mungkin karena rating dianggap lebih berharga daripada rasa hormat.
Padahal, pondok pesantren bukan lembaga sembarangan. Di sana lahir ulama, guru, bahkan pahlawan bangsa. Dari santri tumbuh karakter jujur, tawadhu, dan mandiri — sesuatu yang barangkali sudah langka di ruang redaksi televisi modern. Maka, ketika pesantren dilecehkan, sesungguhnya yang dihina bukan hanya kiai, tapi juga akar moral bangsa sendiri.
Mungkin para kreator di balik tayangan itu perlu sedikit belajar adab sebelum siar. Karena teknologi tinggi tanpa adab hanya melahirkan kebodohan yang viral. Kritis boleh, cerdas harus, tapi beradab itu wajib. Kalau masih belum paham, mungkin mereka perlu mondok sehari saja — agar tahu bedanya ilmu dan olok-olok.
Dan ketika umat sudah muak, jangan salahkan jika televisi kehilangan penontonnya. Sebab masyarakat kita, seburuk-buruknya keadaan, masih tahu mana hiburan yang berisi dan mana yang hanya berisik. Jika media kehilangan rasa hormat, maka sesungguhnya mereka bukan lagi sumber informasi, melainkan sumber kebodohan berjamaah. Dan itu, sayangnya, bukan satire — tapi kenyataan yang getir.
Penulis adalah : Direktur LBH Pendekar, dan Panglima DPP Ormas Gerakan Muslim Penyelamat Aqidah (Gempa)