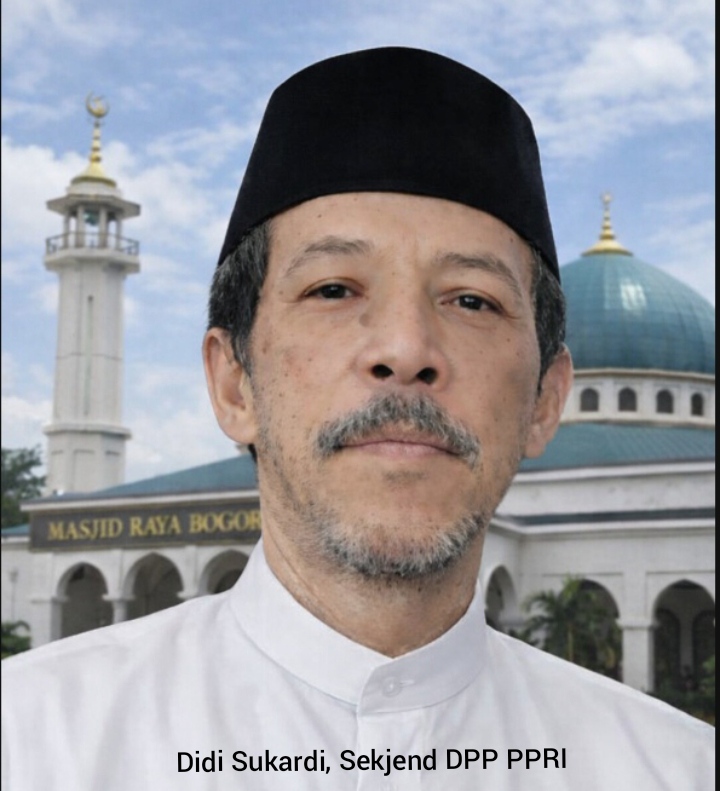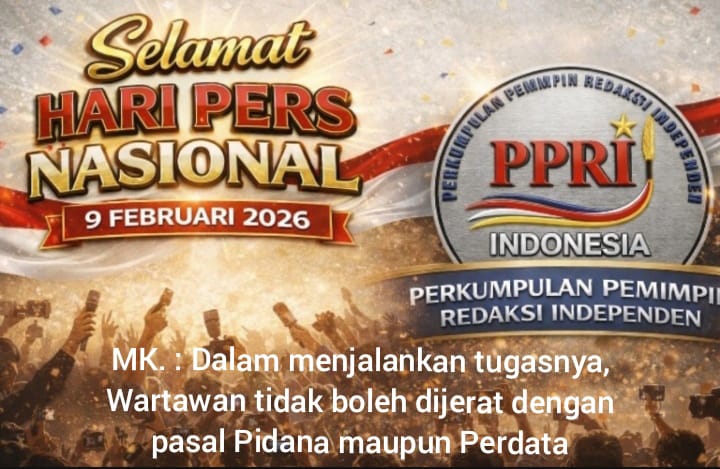Tentang serangga bercahaya; pembangunan yang bising, dan alam yang tak lagi bicara
DEFAKTO /Opini – Menjaga kelestarian kunang-kunang sejatinya bukan soal melindungi serangga kecil yang bercahaya di malam hari. Ia adalah soal menjaga bahasa alam yang paling jujur dan paling sunyi. Kunang-kunang tidak bersuara, tidak berteriak, tidak memaksa. Ia hanya hadir ketika alam masih memberi ruang bernapas. Ketika cahaya kecil itu padam, sesungguhnya alam raya sedang menyampaikan satu pesan: ada yang salah, dan manusia memilih tidak mendengar.
Dulu, kunang-kunang menjadi bagian dari ingatan kolektif pedesaan yang berkelip di sawah, di tepi kebun, di dekat aliran air. Kini, bahkan desa pun kehilangan malamnya. Tanah dipaksa produktif dengan pupuk dan racun kimia, rawa dikeringkan demi kepentingan sesaat, dan ruang lembap tempat larva kunang-kunang tumbuh perlahan dihapus dari peta kehidupan. Yang tersisa hanyalah hasil panen dan laporan produksi, tanpa pernah menghitung apa yang hilang.
Di perkotaan, nasib kunang-kunang bahkan lebih tragis. Mereka tidak mati karena diserang, melainkan karena disingkirkan secara sistematis. Polusi cahaya menjadikan malam tak lagi gelap. Lampu jalan, gedung, reklame, dan simbol kemajuan menyala tanpa jeda, seolah kegelapan adalah aib yang harus dihapus. Padahal, bagi kunang-kunang, gelap adalah syarat hidup. Ketika malam dirampas, kehidupan pun ikut pergi.
Ironisnya, manusia modern gemar berbicara tentang krisis iklim dan kerusakan lingkungan, tetapi mengabaikan tanda-tanda paling awal yang diberikan alam. Para ahli menyebut kunang-kunang sebagai indikator ekosistem yang sehat. Artinya jelas: jika kunang-kunang menghilang, maka yang sakit bukan serangganya, melainkan tanah, air, dan udara tempat manusia berpijak. Namun indikator semacam ini kalah penting dibanding grafik pertumbuhan ekonomi dan target pembangunan.
Pembangunan yang bising sering kali menuntut alam untuk diam. Alam diperlakukan sebagai objek, bukan subjek kehidupan. Ia harus memberi, tapi tidak boleh mengeluh. Ketika serangga bercahaya menghilang, tak ada rapat darurat, tak ada konferensi pers. Sebab kehilangan yang sunyi dianggap bukan ancaman. Padahal, justru dari sunyi itulah kehancuran ekosistem dimulai.
Menjaga kunang-kunang berarti mengembalikan kesadaran bahwa tidak semua yang hidup harus terang, cepat, dan menguntungkan. Ada kehidupan yang hanya bisa bertahan dalam keseimbangan. Mengurangi pestisida, melindungi lahan basah, menyisakan ruang hijau, dan menata pencahayaan malam bukanlah tindakan heroik. Ia hanya soal menahan keserakahan, sesuatu yang tampaknya semakin sulit dilakukan.
Jika suatu hari anak-anak hanya mengenal kunang-kunang dari buku pelajaran atau layar gawai, maka itu bukan sekadar kehilangan serangga. Itu adalah tanda putusnya hubungan batin manusia dengan alam raya. Alam tak lagi menjadi ruang hidup, melainkan sekadar latar belakang pembangunan. Pada titik itu, kerusakan lingkungan berubah menjadi krisis nurani.
Kunang-kunang mengajarkan bahwa cahaya tidak selalu harus menyilaukan untuk bermakna. Cahaya kecilnya lahir dari alam yang seimbang, bukan dari hasrat menguasai alam. Ketika cahaya itu benar-benar padam, mungkin saat itulah kita baru sadar: bukan kunang-kunang yang gagal bertahan, melainkan manusia yang gagal menjaga kehidupan, dan alam raya sedang sekarat.
(Didi Sukardi)