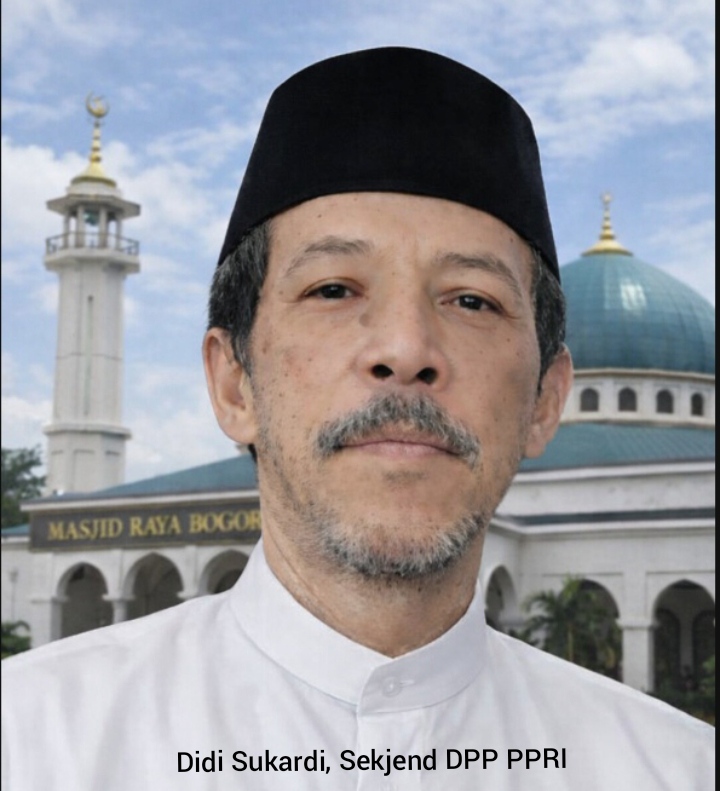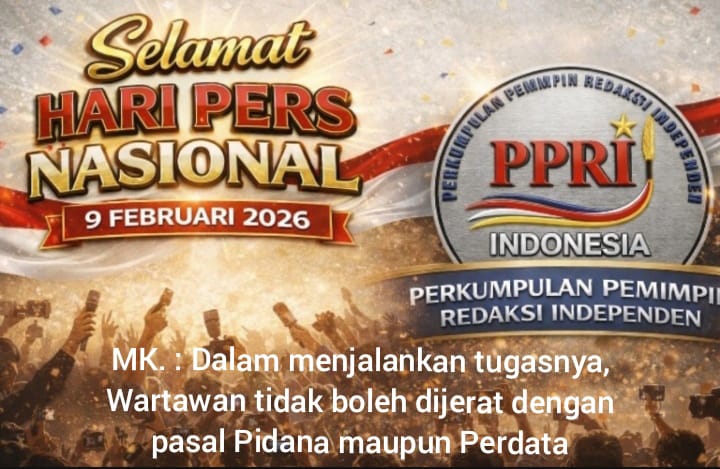Oleh : Didi Sukardi
DEFAKTO / EDITORIAL – Drama foto wartawan berseliweran di grup medsos, dengan narasi pemerasan yang lebih cocok jadi gosip warung kopi ketimbang fakta hukum, kini masuk babak baru. Setelah ramai tudingan ke oknum Intel Polres Bogor, pihak Intel pun angkat bicara: mereka hanya menerima laporan dari Polsek Leuwiliang bahwa wartawan adalah korban pengeroyokan yang diamankan, bukan pelaku pemerasan, apalagi penyebar foto.
Jadi, siapa dalangnya?
Jawabannya: belum jelas.
Pelakunya: belum ketahuan.
Institusinya: belum bersuara.
Tetapi foto wartawannya? Sudah terlanjur jadi komoditas digital.
Ini seperti menonton film aksi tanpa judul: pelaku tidak terlihat, korban berteriak, polisi diam, dan publik dipaksa menebak alur cerita. Bedanya, ini bukan hiburan, ini demokrasi yang sedang digertak dari balik layar.
Foto wartawan tengah bertugas beredar bebas dengan narasi murahan yang mengarahkan opini publik seolah mereka kriminal. Padahal kenyataan di lapangan justru memutarbalikkan logika tuduhan: wartawan itu korban pengeroyokan ketika sedang mengungkap dugaan penggilingan emas ilegal dan peredaran oli palsu. Ironisnya, setelah tubuh mereka jadi sasaran pukulan, nama baik mereka ikut jadi sasaran pencemaran.
Yang lebih memprihatinkan: laporan polisi tanggal 15 Desember, yang seharusnya melindungi hak korban, malah menguap tanpa gaung. Entah tersimpan di map, lemari, laci meja, atau di awan. Yang jelas, respons tuntas belum terdengar.
Di tengah kebingungan ini, publik hanya diberi satu bahan bakar: spekulasi. Di negeri yang katanya taat hukum, persoalan seperti ini seharusnya mudah, tinggal buka suara, jelaskan fakta, sebutkan langkah hukum. Tetapi yang muncul malah sunyi. Sunyi yang terlalu keras untuk tidak disimak.
Dan sementara sunyi itu berlangsung, para wartawan dipaksa menelan stigma: dari korban pengeroyokan berubah menjadi tersangka opini, dan semua berawal dari satu tindakan yang amat sederhana: menyebarkan foto tanpa izin.
Apa ini bentuk baru hubungan aparat dan pers?
“Tidak memukul, tapi membiarkan publik yang memukul dengan opini sesat.”
Kepolisian selalu menuntut objektivitas pemberitaan, tetapi ketika publik menuntut objektivitas penanganan perkara, tiba-tiba semuanya menjadi rumit. Yang seharusnya mudah dibuka, malah rapat disegel. Yang seharusnya diluruskan, malah dibuat berbelit.
Kami tegaskan ulang dengan nada lebih keras: penyebaran foto wartawan tanpa izin, disertai tuduhan liar dan tanpa sumber jelas, bukan hanya pelanggaran etika, ini bentuk persekusi digital. Dan persekusi tidak bisa ditolerir dalam negara yang mengaku menjunjung hukum.
Jika wartawan yang tengah meliput justru dituduh macam-macam, maka pesan yang dikirim ke publik sangat sederhana:
“Siapa pun yang berusaha membongkar kebenaran, bersiaplah dibungkam.”
Dan jika itu benar terjadi, kita sedang menyaksikan demokrasi berjalan mundur, pakai seragam rapi.
Polres Bogor hari ini punya peran penting: membersihkan kabut, menjawab tuntas, bukan membiarkan publik meraba dalam gelap. Karena diam bukan solusi. Diam adalah bensin bagi kecurigaan.
Ini bukan sekadar persoalan foto. Ini soal masa depan kebebasan pers.
Jika persekusi terhadap jurnalis dianggap wajar, maka tunggu saja giliran publik menjadi korban berikutnya.
Karena pers bukan musuh negara, pers adalah cermin. Jika ada pihak yang marah saat bercermin, itu bukan salah kaca. (*)
Penulis adalah : Sekjend DPP Persekutuan Pemimpin Redaksi Independen (PPRI)