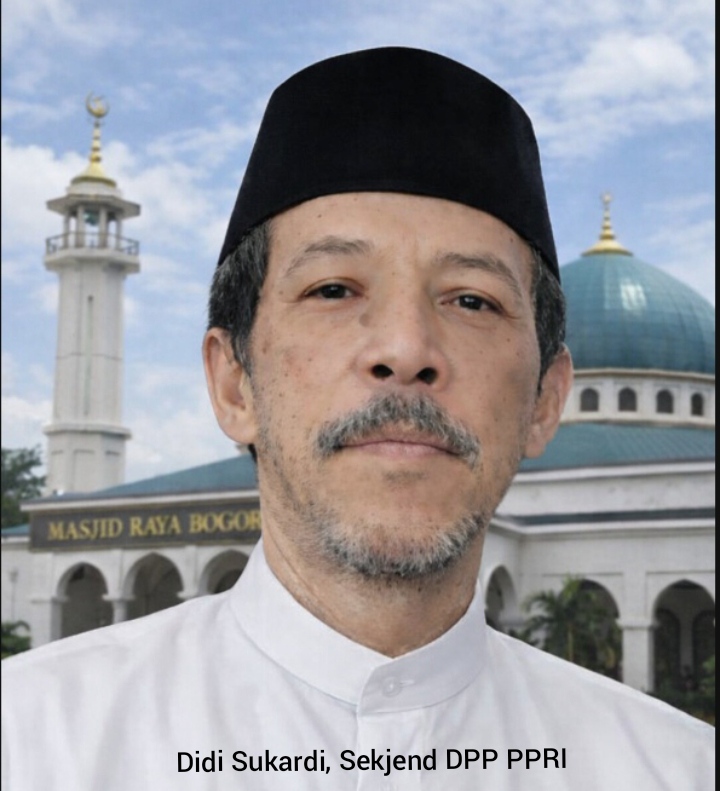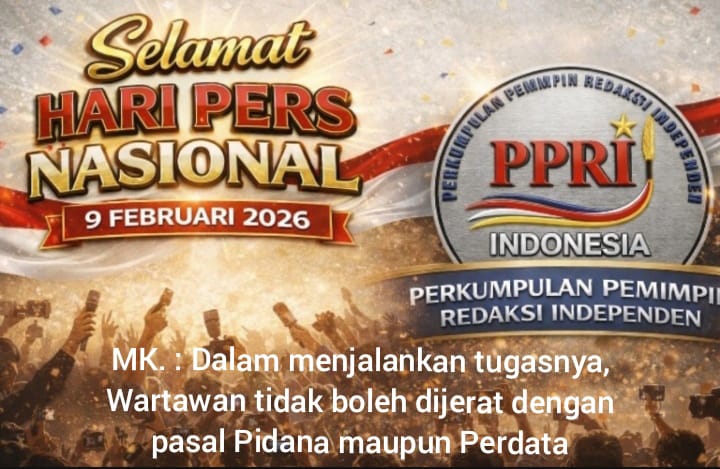Defakto /EDITORIAL – Isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik. Setelah pihak penggugat Roy Suryo dan kawan-kawan memperoleh salinan ijazah sarjana kehutanan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), muncul klaim bahwa dokumen tersebut dapat menjadi bukti baru dugaan pemalsuan. Isu ini cepat berkembang karena menyentuh dua aspek mendasar dalam demokrasi: integritas pejabat publik dan akuntabilitas lembaga negara.
Sekjen Front Penggerak Perubahan Nasional (FPPN) sekaligus aktivis Voice of Banten, Sudrajat Maslahat, menilai KPU harus bertanggung jawab secara profesional dan akuntabel. Namun, dalam konteks ilmiah dan hukum, tudingan semacam ini perlu dikaji hati-hati agar tidak tergelincir menjadi opini tanpa dasar hukum yang sahih.
Tuduhan pemalsuan ijazah adalah perkara serius yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara bagi siapa pun yang dengan sengaja menggunakan atau membuat dokumen palsu. Namun, proses pembuktian dalam hukum pidana tidak bisa berdasar dugaan atau analisis teknis semata.
Metode seperti Error Level Analysis (ELA) yang kerap digunakan publik untuk “mendeteksi” keaslian dokumen digital, tidak memiliki kekuatan hukum bila tidak diverifikasi oleh ahli forensik digital resmi. Oleh karena itu, klaim sepihak di ruang publik tidak bisa dijadikan dasar pembuktian pidana.
Lebih jauh, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) menegaskan bahwa setiap orang, termasuk mantan presiden, harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini penting untuk menjaga keadilan dan mencegah opini publik berubah menjadi penghakiman sosial.
Dalam polemik ini, KPU menjadi sasaran kritik karena dianggap meloloskan calon presiden dengan ijazah bermasalah. Padahal, berdasarkan PKPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tugas KPU dalam tahap verifikasi hanya bersifat administratif, bukan autentikasi forensik.
Selama ijazah yang diajukan calon telah dilegalisasi oleh institusi pendidikan resmi, KPU secara hukum berhak menerima dokumen itu sebagai sah. Maka, menuduh KPU melakukan kelalaian tanpa dasar kuat dapat menyesatkan publik. Kecuali dapat dibuktikan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian berat, KPU tidak bisa dimintai tanggung jawab pidana atas dokumen yang diterima secara prosedural.
Dengan demikian, tanggung jawab hukum bila terjadi pemalsuan ada pada pihak pembuat atau pengguna dokumen palsu, bukan lembaga penerima yang bertindak sesuai mandat administratifnya.
Meski persoalan hukum membutuhkan proses panjang, isu ini tetap menyentuh dimensi etika publik. Berdasarkan Tap MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, pejabat publik wajib menjadi teladan moral dan menjaga kejujuran serta martabat jabatan.
Karena itu, langkah paling etis dalam merespons keraguan publik bukanlah defensif, melainkan transparansi dan keterbukaan informasi. Dalam hal ini, sikap KPU yang membuka akses dokumen kepada pihak penggugat justru mencerminkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan hak publik untuk tahu.
Polemik ijazah palsu sejatinya menjadi ujian bagi kedewasaan publik dan lembaga negara dalam memahami batas antara opini dan fakta hukum. Di satu sisi, masyarakat berhak mengawasi integritas pemimpin. Namun di sisi lain, penegakan hukum dan etika publik harus berjalan dalam koridor ilmiah, objektif, dan tidak digiring oleh sentimen politik.
Kebenaran sejati hanya akan lahir dari proses hukum yang transparan, bukan dari persepsi publik yang penuh prasangka. Dalam negara hukum, keadilan tidak boleh ditentukan oleh opini, tetapi oleh fakta yang dapat dibuktikan.
(Pemimpin Redaksi)